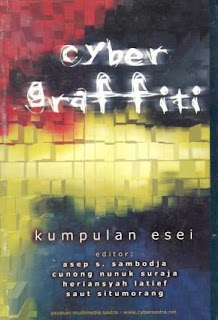
oleh Asep Sambodja
Apa yang diharapkan dari sastrawan cyber di tengah kemelaratan bangsanya? Menjaga nurani. Itu saja. Dan tugas menjaga nurani yang diemban oleh sastrawan-sastrawan cyber sudah memilki arti penting bagi moral bangsa yang kian hari terasa kan terpuruk. Dalam sebuah sajak sederhana yang berjudul “Mata Penyair”, Subagio Sastrowardoyo mengungkap bahwa jika mata penyair itu digunakan sebagaimana mestinya, maka yang dilihatnya adalah kepahitan yang tengah dialami bangsanya, terutama manusia yang berada di sekelilingnya. Ketika ia menutup matanya atau membutakan matanya, maka yang dilihatnya hanya melulu keindahan.
Dengan demikian, menjadi penyair atau sastrawan sesungguhnya lebih merupakan kutukan daripada anugerah atau kehormatan. Ia dikutuk untuk terus menyuarakan kenyataan yang berada di lingkungannya. Dan kenyataan yang tengah dialami bangsa Indonesia saat ini adalah krisis ekonomi, politik, hukum, budaya, atau biasa disebut sebagai krisis multidimensional.
Dalam kondisi seperti ini, para sastrawan ditantang untuk menyuarakan realitas bangsanya. Sastrawan Mochtar Lubis, yang dikenal luas sebagai wartawan jihad, pernah mengatakan bahwa ia tengah menulis sebuah novel yang diberi judul Rayap. Novel tersebut, menurut Mochtar Lubis, bercerita tentang korupsi yang bersimaharajalela di lingkungan birokrasi saat rezim Orde Baru berkuasa. Hingga saat ini, buku tersebut belum kunjung selesai, meskipun Mochtar Lubis sudah mulai sakit-sakitan akibat uianya yang terus beranjak. [Dan kini sudah meninggal dunia, innalillahi wainnailaihi rojiun].
Namun, dari judulnya saja, Rayap, kita sudah bisa menangkap atmosfir yang hendak dibentangkan oleh mantan Pemimpin Redaksi harian Indonesia Raya itu, yang pernah membongkar kasus korupsi di Pertamina, saat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dipimpin oleh Ibnu Sutowo, ayah Ponco Sutowo, salah satu pemilik Hotel Jakarta Hilton Convention Centre (JHCC). Rayap adalah sejenis binatang yang menggerogoti tiang-tiang di rumah atau gedung-gedung, yang lama kelamaan dapat merubuhkan bangunan itu, seberapa pun besarnya bangunan itu.
Di tengah kondisi negara yang mengalami pengeroposan akibat ulah para koruptor, seperti dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai Rp 144,5 triliun, kasus Bank Bali senilai Rp 904,6 miliar, kasus Bank Indover senilai US$ 1 miliar, serta ratusan kasus korupsi lainnya, muncul sastrawan generasi cyber, yang memproklamasikan dirinya pada 9 Mei 2001 dengan menerbitkan buku Graffiti Gratitude.
Apa yang akan diperbuat oleh sastrawan generasi cyber? Sedangkan kedudukan dan fungsi sastrawan tanpa embel-embel cyber pun masih dipertanyakan. Sastrawan di Indonesia belumlah mendapat posisi yang penting dalam masyarakat Indonesia. Mereka masih termaginalisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibandingkan dengan atlet, artis hiburan, dan tentara.
Terbukti, dalam sebuah Temu Sastrawan pada Desember 1982, novelis Y.B. Mangunwijaya mempertanyakan, apa yang bisa diperbuat oleh para sastrawan dan seniman pada umumnya, jika sain dan teknologi sudah mampu menghasilkan pesawat luar angkasa yan mampu kembali ke bumi dengan perhitungan waktu yang hanya berbeda dalam hitungan detik saja?
Dalam artikelnya yang berjudul “Sastra, Sains, dan Teknologi”, Romo Mangunwijaya mengatakan, “Salah satu fungsi penting dari karya sastra, mengantarkan dongeng, hikayat riwayat, mitos, filsafat dalam bentuk cerita dengan rekreasi alternatif-alternatif dunia imajiner selaku pengganti bahan kritik terhadap dunia riil yang ‘cuma begini’ ini, sekarang telah diambil alih (paling tidak sebagian penting) oleh sains dan teknologi. Dapat apa sastra sekarang?”
Pertanaan Romo Mangun itu terasa masih kontekstual dengan kondisi seperti sekarang, di mana negara-negara maju telah membangun stasiun ruang angkasa (international space station), bahkan berhasil mengirim seorang konglomerat Amerika Serikat, Dennis Tito, untuk melancong ke stasiun ruang angkasa tersebut dengan biaya US$ 20 juta, suatu “mahakarya” manusia yang sangat imajinatif dan luar biasa. Apa yang bsa dihasilkan karya sastra?
Pada tahun 1998, ketika Indonesia memasuki masa transisi, saat tumbangnya rezim penguasa Orde Baru, sutradara Teater Koma, N. Riantiarno, juga mempertanyakan hal yang substansinya sama dengan yang ditanyakan Y.B. Mangunwijaya, yakni apakah yang bisa kita perbuat lagi, jika pertunjukan teater di jalanan lebih dahsyat daripada pertunjukan di atas panggung?
Yang dimaksud Nano adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998, di mana banyak toko, terutama milik masyarakat etnis Cina, dan gedung perkantoran dibakar atau dihancurkan oleh massa yang digerakkan entah oleh siapa. Aksi pembakaran itu dikuti dengan aksi penjarahan, seperti semut-semut yang berbaris mengangkut gula pasir, meskipun di antara ribuan massa yang menjarah itu ada yang terpangang api, karena terperangkap dalam mal-mal yang menyala.
Penyair Sapardi Djoko Damono mencoba merekam peristiwa tersebut dalam kumpulan puisinya Ayat-ayat Api, yang sedikit banyak telah merekam kepedihan itu. Dan, upaya itu amat penting artinya, mungkin nanti, meskipun ada yang merasa aneh dengan upaya yang dilakukan Sapardi, di antaranya Afrizal Malna. Sebelumnya, penikmat puisi lebih melihat Sapardi sebagai penyair liris, namun tiba-tiba tampl beda dengan menyoroti kenyataan sosial.
Adanya perubahan dalam ekspresi seorang penyair, baik bentuk maupun isinya, mestinya bukan menjadi sesuatu yang mengherankan, karena hal tu seharusnya menjadi suatu kelaziman bagi sastrawan atau seniman pada umumnya. Perubahan yang drastic sekalipun bukan hal yang aneh dalam duna seni. Presiden penyair Indinesia, Sutardji Calzoum Bachri, memperlihatkan kecenderungan seperti itu. Sejak ia mendeklarasikan Kredo Puisinya, yang intinya membebaskan kata dari beban makna atau ide, kini dapat dikatakan nyaris mengikuti “kredo” Chairil Anwar, yang juga diikuti oleh Goenawan Mohamad, Abdul Hadi W.M., dan Sapardi Djiko Damono, bahwa kata adalah segala-galanya dalam puisi. Sajak Sutardji “Tanah Airmata” memperlihatkan bahwa Sutardji tidak selamanya berpegang teguh pada prinsip bersajak yang diciptakannya sendiri.
Munculnya sastrawan-sastrawan cyber di abad maya ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang luar biasa, karena masih ada orang yang percaya pada sastra di dunia maya. Percaya, bahwa sastra masih perlu ditulis dan dibaca dengan media apa saja, baik media batu, daun lontar, kertas, hingga internet.
Berbagai kemungkinan baru pun bermunculan. Produksi sastra pun mengalir seperti air bah, bukan “banjir puisi” lagi seperti yang dikatakan A. Teeuw dalam menyikapi banyaknya media massa yang memuat karya sastra, terutama puisi. Seorang sastrawan tidak lagi memiliki kendala waktu harus menunggu sekian minggu atau sekian bulan guna melihat karyanya tampil di depan publik. Dengan adanya internet, karya sastra muncul setiap saat, seperti yang terbaca dalam Cybersastra.net dan Bumimanusia.or.id.
Ada atau tidak adanya redaktur sastra atau “polisi sastra” di internet, bukan merupakan kendala, karena sastrawan cyber bisa mengirimkan karyanya ke mana saja, bahkan menyusunnya dalam situs pribadi, seperti yang telah dimiliki oleh Afrizal Malna, Hamid Jabar, T.S. Pinang, Nanang Suryadi, Taufiq Ismail, Pramoedya Ananta Toer, dan Sitor Situmorang.
Pertanyaan mendasar yang ingin mengetahui apa yang bisa diperbuat oleh sastrawan atau penyair-penyair cyber dapat dijawab secara sederhana, bahwa tugas sastrawan di mana pun sama saja, yakni menjaga hati nurani bangsanya. Dan, dalam menjalankan tugas atau ‘tanggung jawab” seagaiana yang sering dilontarkan oleh Sutan Takdir Alisyahbana, tidak ada satu pun seragam yang patut dilekatkan kepada semua sastrawan.
Semuanya mencipta berdasarkan hati nuraninya masing-masing, tidak perlu indoktrinasi segala macam. Karena, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia tidak bisa dibatasi hanya dengan dipakaikan seragam ideologi atau seragam apa pun.
Jika R. William Liddle, dalam pengantarnya untuk buku Catatan Pinggir 3 karya Goenawan Mohamad, mengangap perlunya penulis memiliki “rumah”, maka rumah para penulis atau sastrawan cyber adalah alam maya yang nyaris tiada batasnya itu. Dalam “rumah” yang nyaris tanpa batas, mereka bisa menulis apa saja dan dengan cara apa pun, tanpa adanya rambu-rambu, bahkan tanpa kata-kata sekalipun.
Liddle, dalam tulisannya berjudul "Rumah Seorang Penulis", mengutip penulis Yahudi, Isaac Bashevis Singer, mengatakan, Every writer has an address. Dalam sebuah artikel di The New York Times, sastrawan Amerika Cynthia Ozick juga mengutip pernyataan Isaac Bashevis Singer itu dan mengatakan, “Kalau Anda ingin mengahayati kehidupan yang akan menyebabkan Anda merasa menjadi orang beradab, Anda harus merebutnya melalui budaya Anda sendiri.”
Dalam kondisi Indonesia yang melarat seperti sekarang ini, di mana sastrawan cyber tidak memiliki “rumah” khusus itu, atau bisa jadi tidak akan pernah menunjukkan dirinya dalam kehidupan nyata dan tetap misteri di dunia maya, meskipun terus melahirkan karya-karya imajinatifnya, biasanya bersifat spontas dan apa adanya, apa yang bisa diperbuat jika bukan menyuarakan nurani? ***
Apa yang diharapkan dari sastrawan cyber di tengah kemelaratan bangsanya? Menjaga nurani. Itu saja. Dan tugas menjaga nurani yang diemban oleh sastrawan-sastrawan cyber sudah memilki arti penting bagi moral bangsa yang kian hari terasa kan terpuruk. Dalam sebuah sajak sederhana yang berjudul “Mata Penyair”, Subagio Sastrowardoyo mengungkap bahwa jika mata penyair itu digunakan sebagaimana mestinya, maka yang dilihatnya adalah kepahitan yang tengah dialami bangsanya, terutama manusia yang berada di sekelilingnya. Ketika ia menutup matanya atau membutakan matanya, maka yang dilihatnya hanya melulu keindahan.
Dengan demikian, menjadi penyair atau sastrawan sesungguhnya lebih merupakan kutukan daripada anugerah atau kehormatan. Ia dikutuk untuk terus menyuarakan kenyataan yang berada di lingkungannya. Dan kenyataan yang tengah dialami bangsa Indonesia saat ini adalah krisis ekonomi, politik, hukum, budaya, atau biasa disebut sebagai krisis multidimensional.
Dalam kondisi seperti ini, para sastrawan ditantang untuk menyuarakan realitas bangsanya. Sastrawan Mochtar Lubis, yang dikenal luas sebagai wartawan jihad, pernah mengatakan bahwa ia tengah menulis sebuah novel yang diberi judul Rayap. Novel tersebut, menurut Mochtar Lubis, bercerita tentang korupsi yang bersimaharajalela di lingkungan birokrasi saat rezim Orde Baru berkuasa. Hingga saat ini, buku tersebut belum kunjung selesai, meskipun Mochtar Lubis sudah mulai sakit-sakitan akibat uianya yang terus beranjak. [Dan kini sudah meninggal dunia, innalillahi wainnailaihi rojiun].
Namun, dari judulnya saja, Rayap, kita sudah bisa menangkap atmosfir yang hendak dibentangkan oleh mantan Pemimpin Redaksi harian Indonesia Raya itu, yang pernah membongkar kasus korupsi di Pertamina, saat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dipimpin oleh Ibnu Sutowo, ayah Ponco Sutowo, salah satu pemilik Hotel Jakarta Hilton Convention Centre (JHCC). Rayap adalah sejenis binatang yang menggerogoti tiang-tiang di rumah atau gedung-gedung, yang lama kelamaan dapat merubuhkan bangunan itu, seberapa pun besarnya bangunan itu.
Di tengah kondisi negara yang mengalami pengeroposan akibat ulah para koruptor, seperti dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai Rp 144,5 triliun, kasus Bank Bali senilai Rp 904,6 miliar, kasus Bank Indover senilai US$ 1 miliar, serta ratusan kasus korupsi lainnya, muncul sastrawan generasi cyber, yang memproklamasikan dirinya pada 9 Mei 2001 dengan menerbitkan buku Graffiti Gratitude.
Apa yang akan diperbuat oleh sastrawan generasi cyber? Sedangkan kedudukan dan fungsi sastrawan tanpa embel-embel cyber pun masih dipertanyakan. Sastrawan di Indonesia belumlah mendapat posisi yang penting dalam masyarakat Indonesia. Mereka masih termaginalisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibandingkan dengan atlet, artis hiburan, dan tentara.
Terbukti, dalam sebuah Temu Sastrawan pada Desember 1982, novelis Y.B. Mangunwijaya mempertanyakan, apa yang bisa diperbuat oleh para sastrawan dan seniman pada umumnya, jika sain dan teknologi sudah mampu menghasilkan pesawat luar angkasa yan mampu kembali ke bumi dengan perhitungan waktu yang hanya berbeda dalam hitungan detik saja?
Dalam artikelnya yang berjudul “Sastra, Sains, dan Teknologi”, Romo Mangunwijaya mengatakan, “Salah satu fungsi penting dari karya sastra, mengantarkan dongeng, hikayat riwayat, mitos, filsafat dalam bentuk cerita dengan rekreasi alternatif-alternatif dunia imajiner selaku pengganti bahan kritik terhadap dunia riil yang ‘cuma begini’ ini, sekarang telah diambil alih (paling tidak sebagian penting) oleh sains dan teknologi. Dapat apa sastra sekarang?”
Pertanaan Romo Mangun itu terasa masih kontekstual dengan kondisi seperti sekarang, di mana negara-negara maju telah membangun stasiun ruang angkasa (international space station), bahkan berhasil mengirim seorang konglomerat Amerika Serikat, Dennis Tito, untuk melancong ke stasiun ruang angkasa tersebut dengan biaya US$ 20 juta, suatu “mahakarya” manusia yang sangat imajinatif dan luar biasa. Apa yang bsa dihasilkan karya sastra?
Pada tahun 1998, ketika Indonesia memasuki masa transisi, saat tumbangnya rezim penguasa Orde Baru, sutradara Teater Koma, N. Riantiarno, juga mempertanyakan hal yang substansinya sama dengan yang ditanyakan Y.B. Mangunwijaya, yakni apakah yang bisa kita perbuat lagi, jika pertunjukan teater di jalanan lebih dahsyat daripada pertunjukan di atas panggung?
Yang dimaksud Nano adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998, di mana banyak toko, terutama milik masyarakat etnis Cina, dan gedung perkantoran dibakar atau dihancurkan oleh massa yang digerakkan entah oleh siapa. Aksi pembakaran itu dikuti dengan aksi penjarahan, seperti semut-semut yang berbaris mengangkut gula pasir, meskipun di antara ribuan massa yang menjarah itu ada yang terpangang api, karena terperangkap dalam mal-mal yang menyala.
Penyair Sapardi Djoko Damono mencoba merekam peristiwa tersebut dalam kumpulan puisinya Ayat-ayat Api, yang sedikit banyak telah merekam kepedihan itu. Dan, upaya itu amat penting artinya, mungkin nanti, meskipun ada yang merasa aneh dengan upaya yang dilakukan Sapardi, di antaranya Afrizal Malna. Sebelumnya, penikmat puisi lebih melihat Sapardi sebagai penyair liris, namun tiba-tiba tampl beda dengan menyoroti kenyataan sosial.
Adanya perubahan dalam ekspresi seorang penyair, baik bentuk maupun isinya, mestinya bukan menjadi sesuatu yang mengherankan, karena hal tu seharusnya menjadi suatu kelaziman bagi sastrawan atau seniman pada umumnya. Perubahan yang drastic sekalipun bukan hal yang aneh dalam duna seni. Presiden penyair Indinesia, Sutardji Calzoum Bachri, memperlihatkan kecenderungan seperti itu. Sejak ia mendeklarasikan Kredo Puisinya, yang intinya membebaskan kata dari beban makna atau ide, kini dapat dikatakan nyaris mengikuti “kredo” Chairil Anwar, yang juga diikuti oleh Goenawan Mohamad, Abdul Hadi W.M., dan Sapardi Djiko Damono, bahwa kata adalah segala-galanya dalam puisi. Sajak Sutardji “Tanah Airmata” memperlihatkan bahwa Sutardji tidak selamanya berpegang teguh pada prinsip bersajak yang diciptakannya sendiri.
Munculnya sastrawan-sastrawan cyber di abad maya ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang luar biasa, karena masih ada orang yang percaya pada sastra di dunia maya. Percaya, bahwa sastra masih perlu ditulis dan dibaca dengan media apa saja, baik media batu, daun lontar, kertas, hingga internet.
Berbagai kemungkinan baru pun bermunculan. Produksi sastra pun mengalir seperti air bah, bukan “banjir puisi” lagi seperti yang dikatakan A. Teeuw dalam menyikapi banyaknya media massa yang memuat karya sastra, terutama puisi. Seorang sastrawan tidak lagi memiliki kendala waktu harus menunggu sekian minggu atau sekian bulan guna melihat karyanya tampil di depan publik. Dengan adanya internet, karya sastra muncul setiap saat, seperti yang terbaca dalam Cybersastra.net dan Bumimanusia.or.id.
Ada atau tidak adanya redaktur sastra atau “polisi sastra” di internet, bukan merupakan kendala, karena sastrawan cyber bisa mengirimkan karyanya ke mana saja, bahkan menyusunnya dalam situs pribadi, seperti yang telah dimiliki oleh Afrizal Malna, Hamid Jabar, T.S. Pinang, Nanang Suryadi, Taufiq Ismail, Pramoedya Ananta Toer, dan Sitor Situmorang.
Pertanyaan mendasar yang ingin mengetahui apa yang bisa diperbuat oleh sastrawan atau penyair-penyair cyber dapat dijawab secara sederhana, bahwa tugas sastrawan di mana pun sama saja, yakni menjaga hati nurani bangsanya. Dan, dalam menjalankan tugas atau ‘tanggung jawab” seagaiana yang sering dilontarkan oleh Sutan Takdir Alisyahbana, tidak ada satu pun seragam yang patut dilekatkan kepada semua sastrawan.
Semuanya mencipta berdasarkan hati nuraninya masing-masing, tidak perlu indoktrinasi segala macam. Karena, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia tidak bisa dibatasi hanya dengan dipakaikan seragam ideologi atau seragam apa pun.
Jika R. William Liddle, dalam pengantarnya untuk buku Catatan Pinggir 3 karya Goenawan Mohamad, mengangap perlunya penulis memiliki “rumah”, maka rumah para penulis atau sastrawan cyber adalah alam maya yang nyaris tiada batasnya itu. Dalam “rumah” yang nyaris tanpa batas, mereka bisa menulis apa saja dan dengan cara apa pun, tanpa adanya rambu-rambu, bahkan tanpa kata-kata sekalipun.
Liddle, dalam tulisannya berjudul "Rumah Seorang Penulis", mengutip penulis Yahudi, Isaac Bashevis Singer, mengatakan, Every writer has an address. Dalam sebuah artikel di The New York Times, sastrawan Amerika Cynthia Ozick juga mengutip pernyataan Isaac Bashevis Singer itu dan mengatakan, “Kalau Anda ingin mengahayati kehidupan yang akan menyebabkan Anda merasa menjadi orang beradab, Anda harus merebutnya melalui budaya Anda sendiri.”
Dalam kondisi Indonesia yang melarat seperti sekarang ini, di mana sastrawan cyber tidak memiliki “rumah” khusus itu, atau bisa jadi tidak akan pernah menunjukkan dirinya dalam kehidupan nyata dan tetap misteri di dunia maya, meskipun terus melahirkan karya-karya imajinatifnya, biasanya bersifat spontas dan apa adanya, apa yang bisa diperbuat jika bukan menyuarakan nurani? ***

Tidak ada komentar:
Posting Komentar