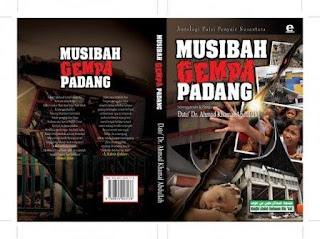Pengantar buku Nyanyian dalam Kelam Sutikno W.S.
oleh Asep Sambodja
Pada 1983, mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Letjen (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo mengajak putra Ketua CC PKI D.N. Aidit, Ilham Aidit, untuk berbicara empat mata, bicara dari hati ke hati. “Ilham, ketika itu, itu adalah tugas buat saya. Ketika itu saya merasa bahwa yang saya lakukan adalah benar. Tapi lama kemudian, berpuluh tahun kemudian, saya sadar, mungkin yang saya lakukan itu keliru. Apakah kamu bisa memahami itu semua?” kata Sarwo Edhie Wibowo kepada Ilham Aidit sebagaimana dituturkan Ilham Aidit dalam film dokumenter Menyemai Terang dalam Kelam karya sutradara I.G.P. Wiranegara (2006) yang diproduksi Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan (LKK) pimpinan Putu Oka Sukanta.
Apakah pengakuan Sarwo Edhie itu benar? Sayang sekali kita tidak bisa mengkonfirmasikan hal penting seperti itu, karena pembicaraan itu hanya di antara mereka berdua, sementara Sarwo Edhie sudah tiada. Sama halnya kita juga tidak bisa mengkonfirmasikan klaim Sarwo Edhie bahwa pasukannya telah membunuh tiga juta orang komunis. Benar tidaknya pengakuan Sarwo Edhie itu, hukum harus tetap ditegakkan dan sejarah harus diluruskan.
Sejarawan Robert Cribb (2005) mengatakan, “Meskipun mantan komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo memperkirakan bahwa tiga juta orang telah terbunuh, kisaran angka yang lebih cenderung betul adalah setengah juta, atau bisa saja setengah atau kelipatan duanya.” Kenapa Robert Cribb menebak-nebak angka seperti itu? Antara lain karena pembunuhan itu dilakukan secara membabi-buta di berbagai tempat. Tapi, pola pembunuhannya sama, yakni setiap malam selama beberapa minggu datang truk yang diparkir di luar suatu tempat penahanan, lalu seorang petugas akan memanggil beberapa nama para tahanan sebanyak tiga, empat, sampai sekitar dua lusin nama. Kadang-kadang korban disungkup kantung beras usang, kadang mereka hanya diberitahu akan dipindahkan ke lokasi lain. Lalu mereka diangkut pergi lima, 10, 30, bahkan sampai 100 km dari tempat penahanan mereka, ke tempat terpencil—hutan, curaman sungai, gua, atau tepi laut. Di sana, di bawah pengawasan beberapa tentara, mereka dibunuh—ditembak, ditusuk, atau dipukul dengan batangan besi—oleh anggota milisi, terkadang setelah disuruh menggali tanah untuk kuburan mereka sendiri (Cribb, 2005: 57-58).
Dalam film dokumenter Mass Grave karya sutradara Lexy Junior Rambadeta (2002), apa yang dikatakan Robert Cribb itu terbukti benar. Pada 16 November 2000, ditemukan kuburan massal di Hutan Situkup, Desa Dempes, Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Jumlah kerangka yang ditemukan ada 21 jenazah, di antaranya kerangka Sandiwijoyo (anggota DPR), Dul Asror (Camat Tempel), Ibnu Santoro (dosen UGM), Marlan (Direktur Waspada), Muhadi, dan Harsono Siswo Sumarto. Mereka ini adalah tahanan tanpa proses pengadilan dari penjara Yogyakarta. Pada 26 Februari 1966 mereka dikirim ke Wonosobo dan dieksekusi pada 3 Maret 1966. Jenazah itu ada yang dikenali melalui cincin kawin yang ditemukan saat penggalian. Cincin itu bertuliskan nama “Sudjijem, 20/6/1965”.
Pramoedya Ananta Toer (dalam Rambadeta, 2002) mengatakan bahwa di Kabupaten Blora ada 5.000 orang pendukung Soekarno yang dibunuh. Pendukung Soekarno itu ada yang berasal dari kalangan nasionalis, agama, dan komunis. “Itu baru satu kabupaten. Belum yang lainnya,” kata Pram.
Belum lama ini, tepatnya pada 17 November 2009, diadakan diskusi buku Lobakan: Kesenyapan Gemuruh Bali ’65 di GoetheHouse, Jakarta. Dalam diskusi tersebut, Dharma Santika Putra mengatakan bahwa cerpen-cerpen yang terhimpun dalam buku Lobakan itu sebagai karya sastra yang gagal. Alasannya karena “beratnya beban yang harus dipikulnya di dalam merebut lembar-lembar sejarah kemanusiaan di Indonesia bahkan mungkin juga dunia” (Putra, 2009).
Saya menilai pernyataan Dharma Santika itu sebagai sebuah pernyataan yang arogan dan gegabah. Apa dasarnya mengatakan cerpen-cerpen yang menyuarakan peristiwa pembantaian massal di Bali pada 1965 itu sebagai karya yang gagal? Adakah karya sastra yang gagal? Bukankah W. Sikorsky (1970) memberi makna baru pada karya-karya Ronggowarsito, Padmosusastro, Muhammad Musa, dan Willem Iskandar tanpa memposisikannya sebagai karya yang gagal? Bukankah Agung Dwi Hartanto (2008) menempatkan Marco Kartodikromo ke tempat terhormat dalam sejarah sastra Indonesia meskipun kolonial Belanda menghinanya sebagai “bacaan liar”? Bukankah filolog-filolog juga memberikan makna baru pada naskah-naskah lama? Kenapa Dharma Santika mengatakan karya sastra itu gagal?
Tampaknya Dharma Santika menggunakan kacamata kuda dalam mengapresiasi karya sastra. Ia tidak berusaha mengaitkan karya itu dengan konteksnya, sehingga muncul penilaian semacam itu. Saya menduga bukan karya itu yang gagal, melainkan Dharma Santika yang gagal menafsirkan cerpen-cerpen yang ditulis Martin Aleida, Putu Oka Sukanta, Putu Fajar Arcana, Putu Satria Kusuma, Sunaryono Basuki K.S., Gde Aryantha Soethama, T. Iskandar A.S., Soeprijadi Tomodihardjo, Fati Soewandi, Ni Komang Ariani, Kadek Sonia Piscayanti, Dyah Merta, May Swan, dan Happy Salma dalam buku Lobakan itu.
Dari sini saya menyimpulkan bahwa untuk memahami karya-karya para sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dengan baik, kita harus mengerti dan memahami sejarah dengan baik pula. Begitu juga kalau kita hendak mengapresiasi karya sastra yang berlatar 1965-1966, maka sejatinya kita juga mengerti betul apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Tanpa mengerti dan memahami sejarah, bisa jadi kita gagal menafsirkan karya sastra yang berlatar sejarah sebagaimana yang dialami Dharma Santika.
Di atas telah saya singgung korban tragedi 1965-1966 yang mati. Bagaimana dengan korban yang masih hidup? Sulami, cerpenis yang juga Sekjen DPP Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang ditahan selama 20 tahun, masih memiliki rasa dendam hingga meninggal terhadap Rezim Soeharto. Penyair Sutikno Wirawan Sigit, yang juga Redaktur Majalah Zaman Baru mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam buku puisi Nyanyian dalam Kelam selama ia dipenjara 10 tahun di Penjara Salemba, Penjara Tangerang, dan Pulau Buru. Sangat banyak yang bernasib sama seperti Sulami dan Sutikno itu.
Dalam film dokumenter Seni Ditating Jaman karya kolaboratif Putu Oka Sukanta, Lilik Munafidah, dan Hendro Sutono (2008), misalnya, ditampilkan dalang Ki Tristuti Rahmadi yang ditahan di Pulau Buru. Menurut Ki Tristuti Rahmadi, selama di Pulau Buru, ia benar-benar merasakan ganasnya hutan di sana. Ia pun menulis beberapa suluk untuk para dalang, termasuk untuk Ki Anom Suroto. Suluk karya Tristuti itu terasa lebih berjiwa karena yang ditulisnya adalah sesuatu yang benar-benar dialaminya, bukan semata-mata dari lamunan.
Kemahiran mendalang Tristuti ini tercium pula oleh aparat keamanan di Pulau Buru. Lalu, ia diminta mendalang oleh petugas karena banyak tahanan Pulau Buru yang mati bunuh diri. Menurut Tristuti, sejak ia mendalang secara rutin di Buru, angka kematian akibat bunuh diri menurun (Sukanta, 2008). Terbaca bahwa wayang sebagai karya seni berfungsi sebagai sarana katarsis ataupun sekadar menjadi eskapisme bagi para tahanan.
Bagi penyair Sutikno W.S. puisi tidak saja berfungsi sebagai media katarsis, tapi juga merekam situasi zaman. Ia yang dipenjarakan oleh Rezim Orde Baru tanpa proses pengadilan sejak 1969 mulai menulis puisi di dalam penjara Salemba pada 1970, di penjara Tangerang pada 1972, dan di Pulau Buru sejak 1973 hingga ia dibebaskan pada 1979. Puisi-puisinya bertarikh 1970-an, masa-masa ia berada dalam penjara, yang terkadang luas langit hanya selebar luas jendela. Mungkin Michel Foucault benar saat ia mengatakan bahwa mengarang itu merupakan upaya untuk menghindari kematian, sebagaimana cerita Seribu Satu Malam yang ditafsirkannya (Heraty, 2000).
Dalam puisi “Nyanyian dalam Kelam”, penyair memposisikan dirinya sebagai orang yang mengamati adanya penindasan. Ia sangat sadar bahwa dirinya termasuk orang-orang yang ditindas, tapi ia sama sekali tidak ingin ditangisi. Bahkan tak ingin dikasihani. Kalaupun harus ada yang ditangisi, maka bumi inilah yang perlu ditangisi, karena bumi merasakan luka dan duka sesama manusia. Bumilah yang menampung setiap tetes darah yang tumpah. Saya melihat Sutikno berhasil mengendapkan peristiwa yang menempatkannya sebagai korban Rezim Orde Baru dengan baik, dan menuangkannya ke dalam puisi dengan diksi yang terjaga dengan baik pula, serta dituturkan secara bersahaja. Ini merupakan kelebihan Sutikno. Ia bisa mendaraskan luka dalam puisi “Nyanyian dalam Kelam” dengan apik.
Nyanyian dalam Kelam
tangisilah bumi ini yang letih dan sengsara
merunduk dalam lecutan siksa dan kesakitan
tangisilah kehidupan ini di mana kuncup-kuncupnya
layu diserap mainan kepalsuan
tetapi jangan kami
orang-orang yang tersisih namun tidak kehilangan hati
untuk mencinta dan mensenyumi dunia
dan bukan kami
anak-anak yang melata di luar sayap induknya
berkubang di tengah musim
mereguk pengap udara
dalam keramahan lagu dan tutur kata
tangisilah kebodohan ini yang sudah
memenjarakan kebenaran
mengepung manusia dalam kecongakan tirani
ya, tangisilah segalanya yang durjana ini demi semua yang akan dilahirkan
dari bayangan kabut dan kandungan kemelut
tetapi jangan kami, o bukan
orang-orang dengan sepotong langit di balik jendela
melihat dunia dalam pelukan kemesraan
tangisilah bumi dan kehidupan ini yang tersedan
dalam kerentanannya
menahan pedihnya cemeti dendam dan kedengkian
ya, tangisilah dunia ini yang tercabik dan merintih karena luka-lukanya
tetapi bukan kami, o tidak
sebab apalah arti kesengsaraan apabila hati rela menggenggamnya
apalah arti perpisahan—dan kebisuan
pabila jantung pun berdebur jua dihangatkan nyala
alangkah banyak derita ini mencacati namamu
o zaman yang memikul sendiri beban anak-anaknya
bermula di kekelaman hari ketika langkah-langkah di
kancah pertarungan
serta menabur, wahai—bagi buminya benih yang akan
melahirkan hari depan
kebebasan terpilih di mana kodrat merdeka melindungi
anak-anaknya
alangkah banyaknya kepiluan ini menjalin jejak kehidupanmu
tapi pun alangkah banyaknya kenangan membekas dalam
selubung kemarakanmu, o kasih yang unggul
yang mengabarkan pada dunia tentang kemuliaan
melagukan manusia serta mengangkat derajatnya
cinta tak terbagi kecuali bagi yang lapar dan terhina
dan air mata pun biarlah tumpah bagi yang tak mengerti
namun memikul juga kesengsaraan ini
anak-anak yang kehilangan orang tua serta kekasih yang
dipunahkan harapannya
rumah-rumah yang diremas sunyi, kegelisahan yang
membludag seperti sampar
dan ketaktahuan—di mana kebenaran bermukim serta
mengembangkan sayap-sayapnya
ya, dan baginya biarlah bumi pun menampung nestapa serta air mata duka
tembang rawan bagi yang tersisih dan disengsarakan
tetapi bukan kami, orang-orang yang terampas namun tak kehilangan daya
untuk menegakkan janji di atas segala kehilangan yang pahit
serta menciptakan
zaman yang marak dilambangi paduan nyanyi
nasi dan melati
(1972—Salemba)
Saya melihat penggunaan judul “Nyanyian” dalam puisi-puisi Sutikno mengandung makna tersendiri. Ia berupaya menghadapi semua peristiwa yang dihadapinya dengan tenang, dengan nyanyian. Upaya ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk untuk menghibur diri agar terlepas dari segala penderitaan. Lagu yang disuarakan memang lagu yang di dalamnya sarat akan luka-luka, penuh kepedihan, namun diam-diam sang pujangga menyusun kekuatan untuk tetap bertahan. Puisi atau karya sastra atau karya seni pada umumnya sejatinya memang memiliki dua fungsi, sebagaimana Horatius (dalam Teeuw, 2003) mengatakan dulce et utile. Pertama, menghibur pembaca atau audiensnya. Kedua, karya itu bermanfaat bagi masyarakat; karya tersebut memberi kekayaan intelektual maupun kekayaan spiritual kepada pembacanya. Puisi-puisi yang lahir dari penjara saya pikir setidaknya memberikan kekayaan spiritual kepada pembacanya. Karena, fakta dan kenyataan diungkapkan secara jujur oleh penyairnya. Dan kejujuran memberikan kontribusi yang sangat besar dalam keindahan sebuah puisi.
Nyanyian Pandak
—untuk trisningku
pabila pita merah
melambai di lekuk ikal rambutmu, nduk
jangan lupakan waktu
ketika kau tangisi kepergian bapakmu
arif diasuh pengalaman
mari ditimba makna perpisahan
yang tahun demi tahun
seperti bajak yang bermain di lumpur waktu
merekatkan getah-getah rindu
namun janganlah melarutkan waktu dengan menunggu
sebab jagung pun
akan berbunga di tiap ladang
dan manusia
menuai hidup dari pekertinya
dan pabila nanti
merah mawar menghias warna langitmu, nakmas
sampirkanlah di sayap-sayap lagu
kasih dan kesetiaan yang tak terkalahkan
dinding penjara dan tanah buangan
(1973—Buru)
Gelap, kelam, senyap, malam, dan sejenisnya adalah kata-kata yang sering muncul dalam puisi-puisi yang lahir di penjara, sebagaimana puisi-puisi Sutikno W.S. Sebagai Redaktur Majalah Zaman Baru, saya pikir Sutikno sangat paham untuk apa sebuah karya sastra diciptakan. Pertanyaan ini juga muncul dari Ni Made Purnamasari dalam diskusi buku Lobakan di GoetheHouse, 17 November 2009. Bahkan Purnamasari menambahkan, apakah karya sastra bisa memberikan solusi untuk pembacanya agar bisa keluar dari kemelut atau keruwetan sejarah ini?
Ya, untuk apa sebuah puisi diciptakan? Dalam konteks Nyanyian dalam Kelam ini, untuk apa Sutikno menciptakan puisi? Apakah puisi-puisi Sutikno bisa memberikan solusi atas persoalan hidup kekinian? Pertanyaan ini saya pikir menarik untuk dijawab. Kalau dilihat dari perspektif sang penyair, minimal ada dua alasan kenapa Sutikno menciptakan puisi. Pertama, penyair yang telah mengalami penderitaan akibat dipenjara selama 10 tahun tanpa pengadilan membutuhkan saluran untuk menuangkan uneg-unegnya, menyuarakan rasa ketidakadilan yang dialaminya, mengingat saluran resmi yang dibikin negara tidak mampu menyalurkan penderitaan warganya seperti itu. Kedua, ada yang hendak dibagi atau diberikan kepada pembaca. Kalau selama ini pemerintah Soeharto memberikan informasi secara sepihak kepada masyarakat, penyair melalui puisi-puisinya menyampaikan informasi lain terhadap kenyataan yang sama dengan perspektif yang berbeda. Puisi-puisi itu memberikan suara lain dalam membaca sejarah.
Kalau dilihat dari perspektif pembaca, apa yang bisa didapat dari puisi-puisi Sutikno itu? Pertama, puisi-puisi Sutikno yang ditulis di dalam penjara pada kurun waktu 1970-an memberikan gambaran baru situasi saat itu dari perspektif sang penyair. Kedua, puisi-puisi Sutikno yang juga survivor ini memberikan kekayaan spiritual kepada pembacanya. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup dari penderitaan, ujian, cobaan yang demikian berat dan mampu melampauinya. Ketiga, puisi-puisi Sutikno enak dinikmati.
Selanjutnya, apakah puisi-puisi Sutikno bisa memberikan solusi bagi pembaca atau masyarakat agar bisa keluar dari persoalan sejarah yang rumit? Secara langsung mungkin tidak. Tapi, secara tidak langsung, puisi-puisi Sutikno bisa memberikan pencerahan kepada pembacanya untuk lebih arif dalam melihat sejarahnya sendiri. Ini penting artinya bagi mereka yang telah direnggut nyawa dan kehormatannya serta penting bagi generasi sesudahnya. Saya sangat ingin mengetahui perasaan algojo-algojo Soeharto yang membunuh sedikitnya 500 ribu bangsanya sendiri pada 1965 itu. Apakah mereka juga merasa seperti Sarwo Edhie Wibowo sebagaimana dituturkan kembali oleh Ilham Aidit? Atau tidak punya perasaan?
Nyanyian Malam
dan pelan kuketuk pintumu
ketika bintang surut
dan malam tidak lagi menyanyi
o alangkah manis rasanya rumah
di mana terukir goresan-goresan lama
tentang engkau dan tentang anak-anak
tentang duniaku belum sudah
dan apabila inilah harinya
ketika panen tiba dan dikau penuainya
apakah lebih indah dari suara-suara
yang menggempitakan langit
menggugurkan dinding kota?
jawabnya adalah tiada
karena betapa ialah yang menyeruku
menjalinkan keharuman cinta
serta kesetiaan pada cita-cita
dan
pabila pelan kuketuk pintumu
ketika bintang surut dan malam tidak lagi menyanyi
adalah ia segumpal damba
yang terbang ke sawang sunyi
mengetuk dinding langit
dan gugur
dalam serpihan hati sendiri
(1974—Buru)
Puisi “Nyanyian Malam” memperlihatkan dengan jelas situasi yang terjadi di dalam dan di luar penjara. Jika pada 15 Januari 1974 kita bisa mengetahui adanya peristiwa huru-hara penolakan modal asing dari Jepang, yang dikenal dengan sebutan seperti nama penyakit, Malari 1974, maka nun jauh di Pulau Buru sana, ada seorang manusia yang terpenjara, yang tengah merindukan rumah dan segala kesentosaannya. Tapi, harapan itu tinggal harapan saja, “dan gugur dalam serpihan hati sendiri”.
Puisi “Ode” yang juga ditulisnya pada 1974 menunjukkan kepenyairan seorang Sutikno W.S. Jujur saja, baru pertama kali ini saya menemukan nama penyair Sutikno W.S. Saya berusaha mencari nama penyair ini dalam beberapa buku sejarah sastra Indonesia, namun nama ini tidak muncul. Dalam biodatanya disebutkan bahwa penyair ini menjadi Redaktur Zaman Baru milik Lekra pada 1964, tapi saya tidak menemukan karya-karyanya pada tahun 1960-an. Dan, ketika Bilven Sandalista dari Penerbit Ultimus Bandung memberikan segepok puisi-puisi Sutikno W.S., saya baru sadar bahwa ternyata masih banyak sastrawan-sastrawan Lekra yang luar biasa.
Dalam hal puisi-puisi Sutikno W.S. ini, pesan yang disampaikannya bukanlah semangat antiimperialisme Amerika sebagaimana yang terbaca dalam puisi-puisi 1960-an. Kenapa yang menjadi tema sentral saat itu antiimperialisme Amerika? Menurut catatan R. Kreutzer (dalam Setiawan, 2003) pada tahun 1948 saja perusahaan-perusahaan swasta Amerika sudah menambang nikel dan bijih besi di Sulawesi; industri pertambangannya di Bangka dan Belitung mengekspor timah dan seng; Rockefeller’s Standard Oil mengebor sekitar 500 ladang minyak mentah di Sumatera; Goodrich dan perkebunan-perkebunan karet raksasa lainnya masing-masing menguasai kurang lebih 100.000 hektare di Sumatera juga. Tapi, yang disuarakan Sutikno adalah suara sepi senyapnya penjara setelah ratusan ribu orang disembelih dan ratusan ribu lainnya, termasuk Sutikno, dipenjara dan diwajibkan korve. Banyak sejarawan yang menyebutkan bahwa Amerika berada di belakang pembunuhan massal yang dilakukan Soeharto dan algojo-algojo Orde Baru.
Ode
apabila inilah hidupku
di mana sawang senyap dan bintang gemerlap
lebur dalam nestapa manusia
serta rimba kelam yang bernyanyi
luluh di desah engah napas-napas yang lelah
apabila lagi yang harus kukatakan
selain menabur cita-cita
meremajakan harapan
sudah tertumpah di sini setumpuk angan
dan mereka yang hilang pun
sudah mencatat pada tapak-tapak tangannya
tentang hari-hari yang surut dan berlalu
serta langit senyap yang memayungi
keabadian cita-cita serta mimpi tunggal angkatannya
sesungguhnya
hari-hari begini panjang
hari-hari begini pekat
tapi pun hari-hari betapa saratnya
di mana setiap orang menghayati kelahiran baru
dalam pribadi
mereka yang kehabisan air mata tetapi bukan cinta
akan hidup yang tidak dipungkiri serta dunia yang dipilihnya
namun adakah kesyahduan lebih syahdu dari nyanyian
yang mengembara di padang-padang kepapaan
dan mengapung seperti doa-doa kudus yang rawan?
ah seandainya ini mengentalkan persahabatan dan meramahkan tutur kata
di mana kelahiran demi kelahiran
ada dalam kehangatan jalinannya
dan apabila inilah hidupku
o dengarlah anak-anak serta kekasih yang menanti
pabila inilah panggilan yang mesti kupenuhi
takkan lagi kuhitung tapak-tapak
juga tangan yang menggeletar lunglai
serta jantung yang mendeburkan rindu demi rindu
pada segalanya yang sirna seperti mainan cahaya yang
disapu senja
tidak, sebab betapa semuanya sudah bagaikan putik
yang mengorak di pangkal pagi
menyalamkan gairah puja bagi dunia
sesungguhnya
inilah mawar dari segenap cintaku
yang setangkai demi setangkai
kusunting di penjuru negeriku
maka apabila inilah hidupku, sepenuhnya
jadilah ia hidup yang bukan menunggu waktu
tapi adalah jalinan suara
dan mainan warna
yang lebur dalam titian cita-cita
dan engkau yang menyertaiku dalam rindu
bukalah hati dan jangan lagi ditangisi, o anak-anak dan kekasih yang menanti
sebab bintang pun belum anti di tengah tasik hidupku ini
(1974—Buru)
Saya merasa nikmat membaca puisi-puisi Sutikno W.S. ini. Dalam arti, apa yang dicita-citakan Lekra melalui Mukaddimah Lekra, yakni tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tampak jelas hadir dalam puisi-puisi Sutikno W.S.***
Citayam, 21 November 2009
Acuan
Cribb, Robert. 2005. “Tragedi 1965-1966 di Indonesia”, dalam Christine Clark et.al. Di Ujung Kelopak Daunnya Tetap Ada Airmata. Yogyakarta: Buku Baik.
Heraty, Toeti (ed.). 2000. Hidup Matinya Sang Pengarang. Jakarta: Buku Obor.
Merta, Dyah et.al. 2009. Lobakan: Kesenyapan Gemuruh Bali ’65. Depok: Koekoesan dan LKK.
Purnamasari, Ni Made. 2009. “Lobakan untuk Fakta dan Fiksi Sejarah”. Makalah diskusi buku Lobakan di GoetheHouse, Jakarta, 17 November 2009.
Putra, Dharma Santika. 2009. “Luka Peradaban yang Dipelihara”. Makalah diskusi buku Lobakan di GoetheHouse, Jakarta, 17 November 2009.
Rambadeta, Lexy Junior. 2002. Mass Grave. Film dokumenter. Jakarta: Offstream.
Sambodja, Asep. 2009. “Historiografi Sastra Indonesia 1960-an: Pembacaan Kritis Karya-karya Sastrawan Lekra dan Manikebu dengan Perspektif New Historicism”. Monografi. Belum diterbitkan.
Setiawan, Hersri. 2003. Negara Madiun?: Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan. Jakarta: FuSPAD.
Sikorsky, W. 1970. Tentang Sejarah Pembentukan Kesusastraan Indonesia Modern. Terj. Koesalah Subagyo Toer. Moskow.
Sukanta, Putu Oka, Lilik Munafidah, dan Hendro Sutono. 2008. Seni Ditating Jaman. Film dokumenter. Jakarta: LKK.
Teeuw, A. 2003. Sastera dan Ilmu Sastera. Jakarta: Pustaka Jaya.
Wiranegara, I.G.P. 2006. Menyemai Terang dalam Kelam. Film dokumenter. Jakarta: Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan.
oleh Asep Sambodja
Pada 1983, mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Letjen (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo mengajak putra Ketua CC PKI D.N. Aidit, Ilham Aidit, untuk berbicara empat mata, bicara dari hati ke hati. “Ilham, ketika itu, itu adalah tugas buat saya. Ketika itu saya merasa bahwa yang saya lakukan adalah benar. Tapi lama kemudian, berpuluh tahun kemudian, saya sadar, mungkin yang saya lakukan itu keliru. Apakah kamu bisa memahami itu semua?” kata Sarwo Edhie Wibowo kepada Ilham Aidit sebagaimana dituturkan Ilham Aidit dalam film dokumenter Menyemai Terang dalam Kelam karya sutradara I.G.P. Wiranegara (2006) yang diproduksi Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan (LKK) pimpinan Putu Oka Sukanta.
Apakah pengakuan Sarwo Edhie itu benar? Sayang sekali kita tidak bisa mengkonfirmasikan hal penting seperti itu, karena pembicaraan itu hanya di antara mereka berdua, sementara Sarwo Edhie sudah tiada. Sama halnya kita juga tidak bisa mengkonfirmasikan klaim Sarwo Edhie bahwa pasukannya telah membunuh tiga juta orang komunis. Benar tidaknya pengakuan Sarwo Edhie itu, hukum harus tetap ditegakkan dan sejarah harus diluruskan.
Sejarawan Robert Cribb (2005) mengatakan, “Meskipun mantan komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo memperkirakan bahwa tiga juta orang telah terbunuh, kisaran angka yang lebih cenderung betul adalah setengah juta, atau bisa saja setengah atau kelipatan duanya.” Kenapa Robert Cribb menebak-nebak angka seperti itu? Antara lain karena pembunuhan itu dilakukan secara membabi-buta di berbagai tempat. Tapi, pola pembunuhannya sama, yakni setiap malam selama beberapa minggu datang truk yang diparkir di luar suatu tempat penahanan, lalu seorang petugas akan memanggil beberapa nama para tahanan sebanyak tiga, empat, sampai sekitar dua lusin nama. Kadang-kadang korban disungkup kantung beras usang, kadang mereka hanya diberitahu akan dipindahkan ke lokasi lain. Lalu mereka diangkut pergi lima, 10, 30, bahkan sampai 100 km dari tempat penahanan mereka, ke tempat terpencil—hutan, curaman sungai, gua, atau tepi laut. Di sana, di bawah pengawasan beberapa tentara, mereka dibunuh—ditembak, ditusuk, atau dipukul dengan batangan besi—oleh anggota milisi, terkadang setelah disuruh menggali tanah untuk kuburan mereka sendiri (Cribb, 2005: 57-58).
Dalam film dokumenter Mass Grave karya sutradara Lexy Junior Rambadeta (2002), apa yang dikatakan Robert Cribb itu terbukti benar. Pada 16 November 2000, ditemukan kuburan massal di Hutan Situkup, Desa Dempes, Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Jumlah kerangka yang ditemukan ada 21 jenazah, di antaranya kerangka Sandiwijoyo (anggota DPR), Dul Asror (Camat Tempel), Ibnu Santoro (dosen UGM), Marlan (Direktur Waspada), Muhadi, dan Harsono Siswo Sumarto. Mereka ini adalah tahanan tanpa proses pengadilan dari penjara Yogyakarta. Pada 26 Februari 1966 mereka dikirim ke Wonosobo dan dieksekusi pada 3 Maret 1966. Jenazah itu ada yang dikenali melalui cincin kawin yang ditemukan saat penggalian. Cincin itu bertuliskan nama “Sudjijem, 20/6/1965”.
Pramoedya Ananta Toer (dalam Rambadeta, 2002) mengatakan bahwa di Kabupaten Blora ada 5.000 orang pendukung Soekarno yang dibunuh. Pendukung Soekarno itu ada yang berasal dari kalangan nasionalis, agama, dan komunis. “Itu baru satu kabupaten. Belum yang lainnya,” kata Pram.
Belum lama ini, tepatnya pada 17 November 2009, diadakan diskusi buku Lobakan: Kesenyapan Gemuruh Bali ’65 di GoetheHouse, Jakarta. Dalam diskusi tersebut, Dharma Santika Putra mengatakan bahwa cerpen-cerpen yang terhimpun dalam buku Lobakan itu sebagai karya sastra yang gagal. Alasannya karena “beratnya beban yang harus dipikulnya di dalam merebut lembar-lembar sejarah kemanusiaan di Indonesia bahkan mungkin juga dunia” (Putra, 2009).
Saya menilai pernyataan Dharma Santika itu sebagai sebuah pernyataan yang arogan dan gegabah. Apa dasarnya mengatakan cerpen-cerpen yang menyuarakan peristiwa pembantaian massal di Bali pada 1965 itu sebagai karya yang gagal? Adakah karya sastra yang gagal? Bukankah W. Sikorsky (1970) memberi makna baru pada karya-karya Ronggowarsito, Padmosusastro, Muhammad Musa, dan Willem Iskandar tanpa memposisikannya sebagai karya yang gagal? Bukankah Agung Dwi Hartanto (2008) menempatkan Marco Kartodikromo ke tempat terhormat dalam sejarah sastra Indonesia meskipun kolonial Belanda menghinanya sebagai “bacaan liar”? Bukankah filolog-filolog juga memberikan makna baru pada naskah-naskah lama? Kenapa Dharma Santika mengatakan karya sastra itu gagal?
Tampaknya Dharma Santika menggunakan kacamata kuda dalam mengapresiasi karya sastra. Ia tidak berusaha mengaitkan karya itu dengan konteksnya, sehingga muncul penilaian semacam itu. Saya menduga bukan karya itu yang gagal, melainkan Dharma Santika yang gagal menafsirkan cerpen-cerpen yang ditulis Martin Aleida, Putu Oka Sukanta, Putu Fajar Arcana, Putu Satria Kusuma, Sunaryono Basuki K.S., Gde Aryantha Soethama, T. Iskandar A.S., Soeprijadi Tomodihardjo, Fati Soewandi, Ni Komang Ariani, Kadek Sonia Piscayanti, Dyah Merta, May Swan, dan Happy Salma dalam buku Lobakan itu.
Dari sini saya menyimpulkan bahwa untuk memahami karya-karya para sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dengan baik, kita harus mengerti dan memahami sejarah dengan baik pula. Begitu juga kalau kita hendak mengapresiasi karya sastra yang berlatar 1965-1966, maka sejatinya kita juga mengerti betul apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Tanpa mengerti dan memahami sejarah, bisa jadi kita gagal menafsirkan karya sastra yang berlatar sejarah sebagaimana yang dialami Dharma Santika.
Di atas telah saya singgung korban tragedi 1965-1966 yang mati. Bagaimana dengan korban yang masih hidup? Sulami, cerpenis yang juga Sekjen DPP Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang ditahan selama 20 tahun, masih memiliki rasa dendam hingga meninggal terhadap Rezim Soeharto. Penyair Sutikno Wirawan Sigit, yang juga Redaktur Majalah Zaman Baru mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam buku puisi Nyanyian dalam Kelam selama ia dipenjara 10 tahun di Penjara Salemba, Penjara Tangerang, dan Pulau Buru. Sangat banyak yang bernasib sama seperti Sulami dan Sutikno itu.
Dalam film dokumenter Seni Ditating Jaman karya kolaboratif Putu Oka Sukanta, Lilik Munafidah, dan Hendro Sutono (2008), misalnya, ditampilkan dalang Ki Tristuti Rahmadi yang ditahan di Pulau Buru. Menurut Ki Tristuti Rahmadi, selama di Pulau Buru, ia benar-benar merasakan ganasnya hutan di sana. Ia pun menulis beberapa suluk untuk para dalang, termasuk untuk Ki Anom Suroto. Suluk karya Tristuti itu terasa lebih berjiwa karena yang ditulisnya adalah sesuatu yang benar-benar dialaminya, bukan semata-mata dari lamunan.
Kemahiran mendalang Tristuti ini tercium pula oleh aparat keamanan di Pulau Buru. Lalu, ia diminta mendalang oleh petugas karena banyak tahanan Pulau Buru yang mati bunuh diri. Menurut Tristuti, sejak ia mendalang secara rutin di Buru, angka kematian akibat bunuh diri menurun (Sukanta, 2008). Terbaca bahwa wayang sebagai karya seni berfungsi sebagai sarana katarsis ataupun sekadar menjadi eskapisme bagi para tahanan.
Bagi penyair Sutikno W.S. puisi tidak saja berfungsi sebagai media katarsis, tapi juga merekam situasi zaman. Ia yang dipenjarakan oleh Rezim Orde Baru tanpa proses pengadilan sejak 1969 mulai menulis puisi di dalam penjara Salemba pada 1970, di penjara Tangerang pada 1972, dan di Pulau Buru sejak 1973 hingga ia dibebaskan pada 1979. Puisi-puisinya bertarikh 1970-an, masa-masa ia berada dalam penjara, yang terkadang luas langit hanya selebar luas jendela. Mungkin Michel Foucault benar saat ia mengatakan bahwa mengarang itu merupakan upaya untuk menghindari kematian, sebagaimana cerita Seribu Satu Malam yang ditafsirkannya (Heraty, 2000).
Dalam puisi “Nyanyian dalam Kelam”, penyair memposisikan dirinya sebagai orang yang mengamati adanya penindasan. Ia sangat sadar bahwa dirinya termasuk orang-orang yang ditindas, tapi ia sama sekali tidak ingin ditangisi. Bahkan tak ingin dikasihani. Kalaupun harus ada yang ditangisi, maka bumi inilah yang perlu ditangisi, karena bumi merasakan luka dan duka sesama manusia. Bumilah yang menampung setiap tetes darah yang tumpah. Saya melihat Sutikno berhasil mengendapkan peristiwa yang menempatkannya sebagai korban Rezim Orde Baru dengan baik, dan menuangkannya ke dalam puisi dengan diksi yang terjaga dengan baik pula, serta dituturkan secara bersahaja. Ini merupakan kelebihan Sutikno. Ia bisa mendaraskan luka dalam puisi “Nyanyian dalam Kelam” dengan apik.
Nyanyian dalam Kelam
tangisilah bumi ini yang letih dan sengsara
merunduk dalam lecutan siksa dan kesakitan
tangisilah kehidupan ini di mana kuncup-kuncupnya
layu diserap mainan kepalsuan
tetapi jangan kami
orang-orang yang tersisih namun tidak kehilangan hati
untuk mencinta dan mensenyumi dunia
dan bukan kami
anak-anak yang melata di luar sayap induknya
berkubang di tengah musim
mereguk pengap udara
dalam keramahan lagu dan tutur kata
tangisilah kebodohan ini yang sudah
memenjarakan kebenaran
mengepung manusia dalam kecongakan tirani
ya, tangisilah segalanya yang durjana ini demi semua yang akan dilahirkan
dari bayangan kabut dan kandungan kemelut
tetapi jangan kami, o bukan
orang-orang dengan sepotong langit di balik jendela
melihat dunia dalam pelukan kemesraan
tangisilah bumi dan kehidupan ini yang tersedan
dalam kerentanannya
menahan pedihnya cemeti dendam dan kedengkian
ya, tangisilah dunia ini yang tercabik dan merintih karena luka-lukanya
tetapi bukan kami, o tidak
sebab apalah arti kesengsaraan apabila hati rela menggenggamnya
apalah arti perpisahan—dan kebisuan
pabila jantung pun berdebur jua dihangatkan nyala
alangkah banyak derita ini mencacati namamu
o zaman yang memikul sendiri beban anak-anaknya
bermula di kekelaman hari ketika langkah-langkah di
kancah pertarungan
serta menabur, wahai—bagi buminya benih yang akan
melahirkan hari depan
kebebasan terpilih di mana kodrat merdeka melindungi
anak-anaknya
alangkah banyaknya kepiluan ini menjalin jejak kehidupanmu
tapi pun alangkah banyaknya kenangan membekas dalam
selubung kemarakanmu, o kasih yang unggul
yang mengabarkan pada dunia tentang kemuliaan
melagukan manusia serta mengangkat derajatnya
cinta tak terbagi kecuali bagi yang lapar dan terhina
dan air mata pun biarlah tumpah bagi yang tak mengerti
namun memikul juga kesengsaraan ini
anak-anak yang kehilangan orang tua serta kekasih yang
dipunahkan harapannya
rumah-rumah yang diremas sunyi, kegelisahan yang
membludag seperti sampar
dan ketaktahuan—di mana kebenaran bermukim serta
mengembangkan sayap-sayapnya
ya, dan baginya biarlah bumi pun menampung nestapa serta air mata duka
tembang rawan bagi yang tersisih dan disengsarakan
tetapi bukan kami, orang-orang yang terampas namun tak kehilangan daya
untuk menegakkan janji di atas segala kehilangan yang pahit
serta menciptakan
zaman yang marak dilambangi paduan nyanyi
nasi dan melati
(1972—Salemba)
Saya melihat penggunaan judul “Nyanyian” dalam puisi-puisi Sutikno mengandung makna tersendiri. Ia berupaya menghadapi semua peristiwa yang dihadapinya dengan tenang, dengan nyanyian. Upaya ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk untuk menghibur diri agar terlepas dari segala penderitaan. Lagu yang disuarakan memang lagu yang di dalamnya sarat akan luka-luka, penuh kepedihan, namun diam-diam sang pujangga menyusun kekuatan untuk tetap bertahan. Puisi atau karya sastra atau karya seni pada umumnya sejatinya memang memiliki dua fungsi, sebagaimana Horatius (dalam Teeuw, 2003) mengatakan dulce et utile. Pertama, menghibur pembaca atau audiensnya. Kedua, karya itu bermanfaat bagi masyarakat; karya tersebut memberi kekayaan intelektual maupun kekayaan spiritual kepada pembacanya. Puisi-puisi yang lahir dari penjara saya pikir setidaknya memberikan kekayaan spiritual kepada pembacanya. Karena, fakta dan kenyataan diungkapkan secara jujur oleh penyairnya. Dan kejujuran memberikan kontribusi yang sangat besar dalam keindahan sebuah puisi.
Nyanyian Pandak
—untuk trisningku
pabila pita merah
melambai di lekuk ikal rambutmu, nduk
jangan lupakan waktu
ketika kau tangisi kepergian bapakmu
arif diasuh pengalaman
mari ditimba makna perpisahan
yang tahun demi tahun
seperti bajak yang bermain di lumpur waktu
merekatkan getah-getah rindu
namun janganlah melarutkan waktu dengan menunggu
sebab jagung pun
akan berbunga di tiap ladang
dan manusia
menuai hidup dari pekertinya
dan pabila nanti
merah mawar menghias warna langitmu, nakmas
sampirkanlah di sayap-sayap lagu
kasih dan kesetiaan yang tak terkalahkan
dinding penjara dan tanah buangan
(1973—Buru)
Gelap, kelam, senyap, malam, dan sejenisnya adalah kata-kata yang sering muncul dalam puisi-puisi yang lahir di penjara, sebagaimana puisi-puisi Sutikno W.S. Sebagai Redaktur Majalah Zaman Baru, saya pikir Sutikno sangat paham untuk apa sebuah karya sastra diciptakan. Pertanyaan ini juga muncul dari Ni Made Purnamasari dalam diskusi buku Lobakan di GoetheHouse, 17 November 2009. Bahkan Purnamasari menambahkan, apakah karya sastra bisa memberikan solusi untuk pembacanya agar bisa keluar dari kemelut atau keruwetan sejarah ini?
Ya, untuk apa sebuah puisi diciptakan? Dalam konteks Nyanyian dalam Kelam ini, untuk apa Sutikno menciptakan puisi? Apakah puisi-puisi Sutikno bisa memberikan solusi atas persoalan hidup kekinian? Pertanyaan ini saya pikir menarik untuk dijawab. Kalau dilihat dari perspektif sang penyair, minimal ada dua alasan kenapa Sutikno menciptakan puisi. Pertama, penyair yang telah mengalami penderitaan akibat dipenjara selama 10 tahun tanpa pengadilan membutuhkan saluran untuk menuangkan uneg-unegnya, menyuarakan rasa ketidakadilan yang dialaminya, mengingat saluran resmi yang dibikin negara tidak mampu menyalurkan penderitaan warganya seperti itu. Kedua, ada yang hendak dibagi atau diberikan kepada pembaca. Kalau selama ini pemerintah Soeharto memberikan informasi secara sepihak kepada masyarakat, penyair melalui puisi-puisinya menyampaikan informasi lain terhadap kenyataan yang sama dengan perspektif yang berbeda. Puisi-puisi itu memberikan suara lain dalam membaca sejarah.
Kalau dilihat dari perspektif pembaca, apa yang bisa didapat dari puisi-puisi Sutikno itu? Pertama, puisi-puisi Sutikno yang ditulis di dalam penjara pada kurun waktu 1970-an memberikan gambaran baru situasi saat itu dari perspektif sang penyair. Kedua, puisi-puisi Sutikno yang juga survivor ini memberikan kekayaan spiritual kepada pembacanya. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup dari penderitaan, ujian, cobaan yang demikian berat dan mampu melampauinya. Ketiga, puisi-puisi Sutikno enak dinikmati.
Selanjutnya, apakah puisi-puisi Sutikno bisa memberikan solusi bagi pembaca atau masyarakat agar bisa keluar dari persoalan sejarah yang rumit? Secara langsung mungkin tidak. Tapi, secara tidak langsung, puisi-puisi Sutikno bisa memberikan pencerahan kepada pembacanya untuk lebih arif dalam melihat sejarahnya sendiri. Ini penting artinya bagi mereka yang telah direnggut nyawa dan kehormatannya serta penting bagi generasi sesudahnya. Saya sangat ingin mengetahui perasaan algojo-algojo Soeharto yang membunuh sedikitnya 500 ribu bangsanya sendiri pada 1965 itu. Apakah mereka juga merasa seperti Sarwo Edhie Wibowo sebagaimana dituturkan kembali oleh Ilham Aidit? Atau tidak punya perasaan?
Nyanyian Malam
dan pelan kuketuk pintumu
ketika bintang surut
dan malam tidak lagi menyanyi
o alangkah manis rasanya rumah
di mana terukir goresan-goresan lama
tentang engkau dan tentang anak-anak
tentang duniaku belum sudah
dan apabila inilah harinya
ketika panen tiba dan dikau penuainya
apakah lebih indah dari suara-suara
yang menggempitakan langit
menggugurkan dinding kota?
jawabnya adalah tiada
karena betapa ialah yang menyeruku
menjalinkan keharuman cinta
serta kesetiaan pada cita-cita
dan
pabila pelan kuketuk pintumu
ketika bintang surut dan malam tidak lagi menyanyi
adalah ia segumpal damba
yang terbang ke sawang sunyi
mengetuk dinding langit
dan gugur
dalam serpihan hati sendiri
(1974—Buru)
Puisi “Nyanyian Malam” memperlihatkan dengan jelas situasi yang terjadi di dalam dan di luar penjara. Jika pada 15 Januari 1974 kita bisa mengetahui adanya peristiwa huru-hara penolakan modal asing dari Jepang, yang dikenal dengan sebutan seperti nama penyakit, Malari 1974, maka nun jauh di Pulau Buru sana, ada seorang manusia yang terpenjara, yang tengah merindukan rumah dan segala kesentosaannya. Tapi, harapan itu tinggal harapan saja, “dan gugur dalam serpihan hati sendiri”.
Puisi “Ode” yang juga ditulisnya pada 1974 menunjukkan kepenyairan seorang Sutikno W.S. Jujur saja, baru pertama kali ini saya menemukan nama penyair Sutikno W.S. Saya berusaha mencari nama penyair ini dalam beberapa buku sejarah sastra Indonesia, namun nama ini tidak muncul. Dalam biodatanya disebutkan bahwa penyair ini menjadi Redaktur Zaman Baru milik Lekra pada 1964, tapi saya tidak menemukan karya-karyanya pada tahun 1960-an. Dan, ketika Bilven Sandalista dari Penerbit Ultimus Bandung memberikan segepok puisi-puisi Sutikno W.S., saya baru sadar bahwa ternyata masih banyak sastrawan-sastrawan Lekra yang luar biasa.
Dalam hal puisi-puisi Sutikno W.S. ini, pesan yang disampaikannya bukanlah semangat antiimperialisme Amerika sebagaimana yang terbaca dalam puisi-puisi 1960-an. Kenapa yang menjadi tema sentral saat itu antiimperialisme Amerika? Menurut catatan R. Kreutzer (dalam Setiawan, 2003) pada tahun 1948 saja perusahaan-perusahaan swasta Amerika sudah menambang nikel dan bijih besi di Sulawesi; industri pertambangannya di Bangka dan Belitung mengekspor timah dan seng; Rockefeller’s Standard Oil mengebor sekitar 500 ladang minyak mentah di Sumatera; Goodrich dan perkebunan-perkebunan karet raksasa lainnya masing-masing menguasai kurang lebih 100.000 hektare di Sumatera juga. Tapi, yang disuarakan Sutikno adalah suara sepi senyapnya penjara setelah ratusan ribu orang disembelih dan ratusan ribu lainnya, termasuk Sutikno, dipenjara dan diwajibkan korve. Banyak sejarawan yang menyebutkan bahwa Amerika berada di belakang pembunuhan massal yang dilakukan Soeharto dan algojo-algojo Orde Baru.
Ode
apabila inilah hidupku
di mana sawang senyap dan bintang gemerlap
lebur dalam nestapa manusia
serta rimba kelam yang bernyanyi
luluh di desah engah napas-napas yang lelah
apabila lagi yang harus kukatakan
selain menabur cita-cita
meremajakan harapan
sudah tertumpah di sini setumpuk angan
dan mereka yang hilang pun
sudah mencatat pada tapak-tapak tangannya
tentang hari-hari yang surut dan berlalu
serta langit senyap yang memayungi
keabadian cita-cita serta mimpi tunggal angkatannya
sesungguhnya
hari-hari begini panjang
hari-hari begini pekat
tapi pun hari-hari betapa saratnya
di mana setiap orang menghayati kelahiran baru
dalam pribadi
mereka yang kehabisan air mata tetapi bukan cinta
akan hidup yang tidak dipungkiri serta dunia yang dipilihnya
namun adakah kesyahduan lebih syahdu dari nyanyian
yang mengembara di padang-padang kepapaan
dan mengapung seperti doa-doa kudus yang rawan?
ah seandainya ini mengentalkan persahabatan dan meramahkan tutur kata
di mana kelahiran demi kelahiran
ada dalam kehangatan jalinannya
dan apabila inilah hidupku
o dengarlah anak-anak serta kekasih yang menanti
pabila inilah panggilan yang mesti kupenuhi
takkan lagi kuhitung tapak-tapak
juga tangan yang menggeletar lunglai
serta jantung yang mendeburkan rindu demi rindu
pada segalanya yang sirna seperti mainan cahaya yang
disapu senja
tidak, sebab betapa semuanya sudah bagaikan putik
yang mengorak di pangkal pagi
menyalamkan gairah puja bagi dunia
sesungguhnya
inilah mawar dari segenap cintaku
yang setangkai demi setangkai
kusunting di penjuru negeriku
maka apabila inilah hidupku, sepenuhnya
jadilah ia hidup yang bukan menunggu waktu
tapi adalah jalinan suara
dan mainan warna
yang lebur dalam titian cita-cita
dan engkau yang menyertaiku dalam rindu
bukalah hati dan jangan lagi ditangisi, o anak-anak dan kekasih yang menanti
sebab bintang pun belum anti di tengah tasik hidupku ini
(1974—Buru)
Saya merasa nikmat membaca puisi-puisi Sutikno W.S. ini. Dalam arti, apa yang dicita-citakan Lekra melalui Mukaddimah Lekra, yakni tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tampak jelas hadir dalam puisi-puisi Sutikno W.S.***
Citayam, 21 November 2009
Acuan
Cribb, Robert. 2005. “Tragedi 1965-1966 di Indonesia”, dalam Christine Clark et.al. Di Ujung Kelopak Daunnya Tetap Ada Airmata. Yogyakarta: Buku Baik.
Heraty, Toeti (ed.). 2000. Hidup Matinya Sang Pengarang. Jakarta: Buku Obor.
Merta, Dyah et.al. 2009. Lobakan: Kesenyapan Gemuruh Bali ’65. Depok: Koekoesan dan LKK.
Purnamasari, Ni Made. 2009. “Lobakan untuk Fakta dan Fiksi Sejarah”. Makalah diskusi buku Lobakan di GoetheHouse, Jakarta, 17 November 2009.
Putra, Dharma Santika. 2009. “Luka Peradaban yang Dipelihara”. Makalah diskusi buku Lobakan di GoetheHouse, Jakarta, 17 November 2009.
Rambadeta, Lexy Junior. 2002. Mass Grave. Film dokumenter. Jakarta: Offstream.
Sambodja, Asep. 2009. “Historiografi Sastra Indonesia 1960-an: Pembacaan Kritis Karya-karya Sastrawan Lekra dan Manikebu dengan Perspektif New Historicism”. Monografi. Belum diterbitkan.
Setiawan, Hersri. 2003. Negara Madiun?: Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan. Jakarta: FuSPAD.
Sikorsky, W. 1970. Tentang Sejarah Pembentukan Kesusastraan Indonesia Modern. Terj. Koesalah Subagyo Toer. Moskow.
Sukanta, Putu Oka, Lilik Munafidah, dan Hendro Sutono. 2008. Seni Ditating Jaman. Film dokumenter. Jakarta: LKK.
Teeuw, A. 2003. Sastera dan Ilmu Sastera. Jakarta: Pustaka Jaya.
Wiranegara, I.G.P. 2006. Menyemai Terang dalam Kelam. Film dokumenter. Jakarta: Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan.