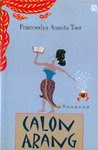oleh Asep Sambodja
“Tukang pidato adalah seniman,” kata Njoto alias Iramani, menerjemahkan pernyataan Multatuli, “Ook de redenner is een kunstenaar.” Paling tidak, DN Aidit yang dikenal dunia internasional sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) itu juga menulis puisi.
Ada sembilan puisi DN Aidit yang terdapat dalam buku Gugur Merah: Sehimpunan Puisi Lekra, Harian Rakyat 1950-1965 yang dihimpun Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, yang terbit pada bulan September 2008. Sebenarnya jumlah puisi Aidit lebih banyak dari itu, hanya saja ada puisi-puisi Aidit yang tidak lolos dari redaksi Harian Rakyat Minggu, Amarzan Ismail Hamid, yang kini menjadi redaktur senior Tempo dengan nama Amarzan Loebis.
Dari kesembilan puisi itu, ada satu puisi yang sepertinya tidak utuh karena kertas Koran Harian Rakyat itu sudah dimakan rayap, yakni puisi yang berjudul “Jauhilah Imperialis AS”, yang ditulis pada 20 Juli 1965. Meskipun demikian, pesan yang ingin disampaikan Aidit melalui puisi itu jelas tertangkap, yakni meminta Amerika Serikat menghentikan agresinya di Vietnam.
Kedelapan puisi Aidit yang lainnya adalah “Hanya Inilah Jalannya”, “Sekarang Ia Sudah Dewasa”, “Yang Mati Hidup Kembali”, “Kidung Dobrak Salahurus”, “Sepeda Butut”, “Untukmu Pahlawan Tani”, “Tugas Partai”, dan “Ziarah ke Makam Usani”.
Dari judulnya saja sudah cukup terbaca dengan terang-benderang pesan apa yang hendak disampaikan oleh penyair DN Aidit ini. Memang, kebijakan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan redaksi Harian Rakyat tidak mengharamkan puisi pamflet. Justru yang dihindari itu adalah puisi-puisi yang dinilai dekaden, klangenan, dan kosong melompong. Konsep seni Lekra adalah 1-5-1, dalam arti “Politik adalah panglima”, “5 kombinasi”, dan “Turun ke bawah”.
Yang dimaksud 5 kombinasi di sini adalah: (1) meluas dan meninggi, (2) tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, (3) tradisi baik dan kekinian revolusioner, (4) kreativitas individual dan kearifan massa, (5) realisme sosialis dan romantik revolusioner.
Dengan kata lain, kelima kombinasi itu menjadi dasar dalam kerja kreatif seniman Lekra dengan payung “politik adalah panglima”. Dan, itu hanya bisa diwujudkan kalau senimannya itu langsung turun ke bawah, langsung merasakan denyut nadi rakyatnya, baik nelayan, petani, buruh, prajurit, pegawai, atau katakanlah kaum wong cilik.
Nah, konsep seperti itulah yang terbaca dalam puisi-puisi DN Aidit ini. Ia, misalnya, langsung bersimpati pada orang-orang kecil yang mati memperjuangkan haknya. Dalam puisi “Untukmu Pahlawan Tani” Aidit menuliskan /kutundukkan kepala/ untukmu pahlawan/ pahlawan tani boyolali. Jelas, bahwa yang dikatakan Aidit dalam puisinya itu memiliki konteks, yakni peristiwa penembakan petani yang terjadi pada 18 November 1964, yang menewaskan tiga petani, yakni Jumari, Sonowiredjo, dan Partodikromo.
Peristiwa penembakan petani itu cukup terekspos secara nasional, sehingga yang merespons peristiwa itu melalui puisi bukan hanya DN Aidit. Penyair lainnya yang juga menulis puisi dengan konteks yang sama adalah Sitor Situmorang, yang menulis "Pesan 3 Petani Boyolali", Budi Santosa Djajadisastra yang menulis "Ketahon--Suatu Titik Balik", dan Amarzan Ismail Hamid yang menulis "Boyolali". Amarzan tidak hanya menulis puisi mengenai hal ini. Dalam buku Laporan Dari Bawah:Sehimpunan Cerita Pendek Lekra, Harian Rakyat 1950-1965 (yang juga disusun oleh Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan), Amarzan juga menulis cerpen dengan judul yang sama, "Boyolali". Bahwa ketiga petani itu mati karena memperjuangkan haknya untuk mendapatkan bagi hasil yang sama antara petani dengan pemilik tanah ('tuan tanah') Wirjowiredjo, yakni 1:1 sesuau UU Pokok Agraria. Sayang, ketiga petani itu ditembak mati.
Demikian pula dalam puisi “Ziarah ke Makam Usani”, Aidit menulis /semua kawan tunduk berdiri/ duka cita menyayat hati/ airmata mengalir, butir demi butir/ dan semua berjanji/ akan nyalakan api juang usani …usani pergi, api juangnya nyala abadi/ PKI mekar harum mewangi. Sekali lagi, konteksnya jelas, yakni Usani, seorang perempuan yang mungkin dianggap biasa-biasa saja, tapi di mata seorang ketua partai politik terbesar keempat di Indonesia diberi penghargaan yang demikian terhormat. Aidit menyebutnya, “Wanita pejuang komunis, pembela setia buruh dan tani, yang mati dalam pengabdiannya sebagai proletariat sejati.”
Dalam puisi “Ziarah ke Makam Usani” ini, Aidit juga memasukkan ideologinya atau ideologi partainya, yakni “Mengganyang si lima jahat”. Kelima “lawan” yang dianggap “jahat” itu adalah (1) “Malaysia”, (2) kabir, (3) 7 setan desa, (4), imperialis AS, (5) Revisionis.
Presiden Soekarno pada 3 Mei 1964 mengeluarkan kebijakan mengenai Dwikora, yang terdiri dari: pertama, “Ganyang Malaysia”, yang dianggap sebagai negara bentukan neokolonialis Inggris, dan kedua, membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Kebijakan ini ditafsir Aidit sebagai lawan yang harus dihadapi, terutama untuk pembentukan negara federasi Malaysia.
Kabir atau Kapbir adalah akronim dari Kapitalis Birokrat, yakni para purnawirawan militer yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan negara, sehingga mengakibatkan mismanagement yang akrab dikenal dengan “salah urus”. Bisa dibayangkan jika Aidit jadi presiden seandainya menang dalam pemilihan umum, maka para purnawirawan militer itu akan dibersihkan dari perusahaan-perusahaan. Makanya, dengan menjadikan kabir sebagai musuh, Aidit dan PKI pun berhadapan dengan militer, terutama Angkatan Darat.
Tujuh setan desa juga dimaksudkan Aidit dan PKI untuk memudahkan warga desa mewaspadai musuh-musuhnya. Ketujuh setan desa yang dimaksud adalah (1) tuan tanah, (2) lintah darat, (3) tengkulak jahat, (4) tukang ijon, (5) bandit desa, (6) pemungut zakat, (7) kapitalis birokrat desa. Untuk poin nomor 6, tentu saja menyebabkan massa PKI di desa berhadapan dengan massa Islam, karena membayar zakat itu merupakan kewajiban sebagai seorang muslim, sama halnya dengan melakukan ibadah sholat atau puasa, serta naik haji bagi yang kaya. Dibandingkan seruan menyerang 3 setan kota, seruan mengganyang 7 setan desa ini lebih bergemuruh di bawah. Dampaknya adalah terjadi konflik horisontal di level akar rumput, mirip dengan konflik di Ambon dan Sambas.
Dengan menempatkan imperialis AS sebagai musuh, meskipun hingga kini kita masih melihat “kreativitas” Amerika di Afghanistan dan Irak, sudah pasti PKI berhadapan dengan Amerika, lengkap dengan mata-matanya. Kalau dalam penelitian Asvi Warman Adam mengenai peristiwa G 30 S 1965 disebutkan adanya keterlibatan CIA, hal itu merupakan sesuatu yang niscaya. Demikian pula dengan menempatkan kaum Revisionis, kalangan yang tidak sejalan dengan paham Revolusi belum selesai, sebagai musuh, maka Aidit dan PKI serta merta membuat jurang pemisah yang semakin dalam.
Dari puisi “Ziarah ke Makam Usani” itu pula Aidit memperlihatkan bahwa api juang Usani, semangat Usani dan kaum proletar lainnya, bahkan semangat partai komunis demikian tumbuh bergelora. Semangat seperti inilah yang membuat hidup lebih hidup, membuat hidup penuh taste, sama sekali tidak menciptakan generasi yang enjoy aja.
Hanya saja, kita tahu, bahwa kita tidak hidup di lingkungan yang homogen. Meminjam kata-kata Utuj Tatang Sontani, “sayang ada orang lain”. Dan lagi, pengaruh globalisasi juga bisa terasa sampai di dapur dan tempat tidur kita. Perang Dingin antara Amerika dengan Uni Soviet terasa juga sampai di Jakarta, sampai ke Lubang Buaya, sampai pula pada pembunuhan massal orang PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Kenapa di Jawa Barat, yang notabene berjarak paling dekat dengan Lubang Buaya, tidak ada pembantaian massal terhadap orang-orang PKI? Dari penelitian Ben Anderson terbaca bahwa Pangdam Siliwangi saat itu, yakni Ibrahim Adjie, tidak mengizinkan RPKAD beroperasi di wilayahnya. Siapa yang menggerakkan RPKAD saat itu? Siapa yang berani bertanggung jawab?
Aidit pun mati. Ia menjadi salah satu target yang diburu. Ia diburu seperti Amerika memburu Osama bin Ladin. Osama, bukan Obama. Meskipun Aidit mati, karyanya akan tetap abadi. Karyanya akan terus dibaca. Karena, di balik karyanya, sesungguhnya Aidit ingin bicara banyak. Tukang pidato yang ingin jadi penyair itu boleh saja dihilangkan, tapi pesan yang ingin disampaikan masih terpelihara hingga kini.
Berikut saya kutipkan sebuah sajak lengkap Aidit, “Kidung Dobrak Salahurus”, yang tetap memperlihatkan garis ideologi dan keyakinan politiknya yang demikian kental.
Kidung Dobrak Salahurus
Kau datang dari jauh adik
Dari daerah banjir dan lapar
Membawa hati lebih keras dari bencana
Selamat datang dalam barisan kita
Di kala kidung itu kau tembangkan
Bertambah indah tanah priangan
Sesubur seindah priangan manis
Itulah kini partai komunis
Tarik, tarik lebih tinggi suaramu
Biar tukang-tukang salahurus mengerti
Benci rakyat dibawa mati
Cinta rakyat pada pki
Teruskan, teruskan tembangmu
Bikin rakyat bersatupadu
Bikin priangan maju dan jaya
Alam indah rakyat bahagia
Cipanas, 13 Januari 1963
Apa yang ditulis penyair Aidit di atas tidak jauh beda dengan apa yang diucapkan para calon presiden Indonesia sekarang ini. Baik yang kita baca di media massa atau yang kita tonton di iklan televisi. Jadi, sama saja. Siapa pun ketua partai politiknya, siapa pun yang ingin menjadi penguasa, suaranya akan sama seperti itu. Inilah puisi pamflet. Dan itu sah saja, meskipun bukan satu-satunya. ***